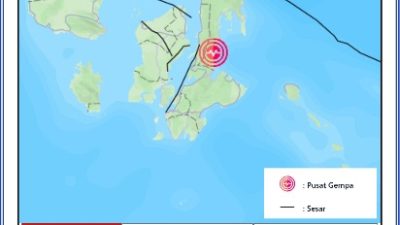“Siapapun yang diberi kekuasaan, pasti menyalahgunakannya. Tidak perduli apakah dia seorang pangeran atau rakyat jelata. Kecuali, dia menjiwainya dengan cinta kebenaran & kebajikan”. (Jean De La Fontaine – Sastrawan Prancis)
“Pengabdianku, Setetes Air di Gurun”. Itulah judul opini yang dimuat di halaman depan Surat Kabar Harian Republika di salah satu Edsi Januari 1993.
Sepenggal kalimat yang mengundang minat baca. Wajar, jika perhatianku–yang kala itu bekerja sebagai redaktur media lokal–langsung tersedot untuk menyimak lebih jauh.
Membacanya lebih saksama. Mencoba memahami nilai-nilai integritas serta kecintaan mendalam penulis opini itu terhadap profesi dan jabatan yang diembannya, kala itu.
Terlebih opini itu, buah goresan pena salah seorang perwira polisi terbaik. Yang pernah dimiliki bangsa ini: Kapolri, Jenderal (Pol.) Koenarto.
Angel opini singkat Koenarto yang pernah jadi Ajudan Presiden Soeharto itu, adalah gambaran ketidakberdayaannya dalam penegakan hukum. Coba simak salah satu paragrafnya:
“Saya pernah melihat wajah penegakan hukum di negeri ini sudah hitam sehitam-hitamnya. Dalam situasi serba gelap demikian obsesi terakhir saya hanyalah, kegelapan itu kurang satu: saya”.
Koenarto kemudian segera menghadap Presiden, Soeharto, dan ingin mengajukan pengunduran dirinya sebagai Kapolri. Tetapi katanya, Soeharto
“”menahannya” dengan argumentasi yang sangat menohok Koenarto.
“Koenarto, kamu mesti menyadari. Membangun hukum di negeri ini, sama dengan membangun rumah. Kita tengah proses membangun. Rumah yang belum selesai pintu dan jendelanya adalah celah bagi maling…”
Motivasi Koenarto menggelegar. Meski menyakitkan, kangker harus dioperasi. Lantas, terjadilah pembenahan moral polisi secara signipikan.
Polda Jawa Barat dijadikan basis pembinaan polisi nakal. Sebuah kalimat menggetarkan hati jadi motto Polri: “Tekadku Pengabdian Terbaik”.
Para pakar kepolisian, kriminolog dan sosiolog dikumpul Koenarto untuk sebuah penelitian seputar ethik (moral) kepolisian. Untuk menjawab sepotong pertanyaan: kenapa polisi nakal bisa muncul?
Ironis, kesimpulan penelitian itu yang justru lebih mengejutkan: “Tujuh puluh lima persen kejahatan polisi bersumber dari masyarakat…”
Kita tidak tahu persis. Apakah kesimpulan penelitian itu masih relevan hingga kini. Yang pasti, 15 tahun sebelumnya (1978) korupsi besar-besaran di tubuh Polri, yang melibatkan Wakapolri, Letjend. (Pol.) Soewiji telah menciptakan situasi pelik: Polisi menyidik Polisi.
Ketegasan Kapolri kala itu, Widodo Budidarmo, plus dorongan mantan Kapolri Hoegeng, telah mengantar Wakapolri dan beberapa Perwira Polisi yang terlibat untuk duduk di kursi pengadilan.
Mereka kemudian divonnis penjara dan dipecat. Padahal, Mehankam/Pangab, Jend. Maraden. Panggabean kala itu, telah meminta agar kasus itu diselesaikan secara internal.
Tetapi, Widodo tetap dengan tekadnya. Lantas, pembersihan Polri dari prilaku polisi nakal, tidak bisa dihindari. Revormasi total.
Tragedi penembakan opsir polisi di rumah jenderal polisi, awal Juli 2022 silam yang menewaskan Brigadir Joshua Hutabarat, memaksa Polri menerapkan (kembali) kebijakan ala peristiwa 1978 itu: Polisi menyidik Polisi.
Ironis, hingga kasus ini disidang, toh motif pembunuhan opsir polisi yang telah menjadikan jenderal bintang dua jadi terancam hukuman mati, tak kunjung terungkap.
Yang mungkin disepakati adalah bahwa sikap dasar peristiwa ini tetaplah seputar adagium kemerosotan moral yang sudah sejak lama tersemai di tubuh Polri.
Jika diamati saksama keprihatinan Koenarto dalam opini di atas: “Penegakan Hukum Indonesia hitam se hitam-hitamnya,” mungkin merupakan akar dari kondisi dekadensi moral Polri, hari ini.
Terlepas belum terungkapnya, motif pembunuhan itu, setidaknya telah membuka tabir penyebab menurunnya integritas Polri yang diduga membungkus berbagai bentuk kejahatan yang dilakoni sekelompok perwira polisi. Tentu, dengan lebih dulu menerabas rambu-rambu ethik profesi mereka.
Lantas, pengamat melirik peran Satuan Petugas Khusus (Satgasus) Merah Putih dengan kewenangan eksklusif. Diduga dari sini menebar penyimpangan kewenangan di bawah komando Irjen Ferdi Sambo.
Analisis para pemerhati kepolisian mensiyalir institusi yang dibentuk Tito Karnavian ini, tampil sebagai skuad dengan segala arogansinya.
Tugas suci yang diharapkan justru mengkoordinir black-market perjudian on-line dengan dugaan imbal income di angka spektakuler.
Untungnya, institusi ini, mendadak dibubarkan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, menyusul kasus tertembaknya Brigadir J di Rumah Dinas Irjen Ferdi Sambo.
“Tetapi, gurita kejahatannya masih menjalar ke mana-mana,” ujar seorang pengamat. Jenderal bisa saja dihukum mati. Tetapi kejahatan yang diwariskannya, tetap hidup abadi.
Tends Power to Corrupt di institusi Polri mulai terbuka pasca kematian Brigadir J. Kalangan religius skeptis: inilah cara “Langit” mempertontonkan lalu-lintas mafia yang berseliweran di tubuh Polri.
Penggelindingan dana-dana haram ini menjadi “liar” dengan konsekuensi lahirnya berbagai bentuk kejahatan baru dengan target meraih kehidupan glamour dan hura-hura. Wanita dan harta, adalah sisi lain fenomena itu. Sisi gelap, pastinya.
Kondisi demikian, memaksa “pemain” tercerabut dari tugas hakiki. Konsekuensi logis yang mengemuka justru sikap polisi yang materialistis semata. Jika sudah demikian parahnya akan muncul sebuah harapan: Bisakah kita aman tanpa polisi?
Presenter Nasional Nazwa Shihab kemudian “menggoreng” situasi ini untuk menarik simpati publik anti polisi hedon. Sayangnya, hanya sebatas menyumbat air di hilir. Akarnya, malah tak tersentuh. No solution.
“Semua kejahatan didasari oleh kerusakan moral”.
Mungkin sebagian kita setuju dengan ungkapan itu. Legitimasi atas dogma ini menuntut solusi holistik. Setidaknya, mengingatkan kita pada simpulan penelitian Koenarto di atas: 75 % kejahatan polisi bersumber dari masyarakat.
Untuk itu, setuju atau tidak: untuk menjadikan Polri sebagai institusi penegak hukum berintegritas, tidak semata tanggung jawab Kapolri dan segelintir perwira yang masih loyal pada ethik profesi. Tetapi, sangat bergantung pada political will masyarakat Indonesia sendiri.
Indonesiais, Prof.Daniel S.Lev Guru Besar Universitas Washington sudah mewanti-wanti ini di era Orde Baru.
Ketika memberi “”Pengantar” pada Buku Catatan Hukum karya Karni Ilyas, Daniel mengajukan pertanyaan:
“Jika ingin melakukan revormasi hukum di Indonesia pihak mana yang lebih dulu direformasi? Masyarakat atau Aparat nya?”
Pekerti yang jadi obsesi kita sesungguhnya, sederhana saja: Polri mesti memberi jaminan rasa aman bagi publik. Hanya itu. Tentu, obsesi itu mewujud jika pihak Polri sendiri lah yang jadi inisiatornya dari internal mereka.
Formulasinya sederhana. Kembalilah pada motto Koenarto yang memang terkesan sloganistis. Tetapi, punya makna yang “dalam”:
“Tekadku Pengabdian Terbaik”.
Drs.Wahyudi El Panggabean, M.H., Wartawan Senior & Direktur Utama, Lembaga Pendidikan Wartawan, Pekanbaru Journalist Center (PJC).